 Lukas Benevides, Peneliti Suryakanta Institute.(Dok. Pribadi)
Lukas Benevides, Peneliti Suryakanta Institute.(Dok. Pribadi)
DEMONSTRASI massal di depan kantor DPR RI hingga meluas ke berbagai sudut Jakarta Senin (25 Agustus 2025) sebenarnya dipicu alasan sederhana: anggota DPR ingin mendapatkan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Massa menuntut pembatalan agenda tersebut, bahkan pembubaran lembaga DPR. Amarah massa semakin tersulut lantaran petinggi DPR yang meremehkan aspirasi pembubaran DPR.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Sudah banyak tulisan menggubris hitung-hitungan pendapatan seorang anggota DPR yang mencapai sekitar Rp230 juta per bulan. Tulisan ini tidak bermaksud menambah barisan kalkulasi matematis ini, tetapi berfokus ke alasan di balik tuntutan itu dari sudut ekonomi politik.
Imbas Kebijakan Prabowo
Alasan tunjangan rumah anggota DPR Rp50 juta per bulan memicu amarah tak terkontrol warga adalah wacana yang mencuat ketika warga tengah tercekik secara ekonomi. Kebijakan Prabowo memicu naiknya harga barang sekaligus menyusutnya lapangan kerja.
Potret ini berbeda sekali dengan pidato retorik Prabowo pada sidang tahunan MPR RI Jumat 15 Agustus 2025 yang mengklaim tingkat pengangguran berkurang dan banyak lapangan kerja baru tercipta. Alih-alih efisiensi, justru berujung miskalkulasi kebijakan yang sentralistik, top-down, mengurangi daya beli pasar, meningkatkan pengangguran dan kenaikan biaya hidup (Amelia dkk, 2025).
Efisiensi menuntut penggunaan sedikit sumber daya untuk hasil yang lebih besar. Yang terjadi pada kebijakan efisiensi Prabowo justru inefisiensi. Demonstrasi anarkistis Senin 25 Agustus 2025 seharusnya tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi terutama terhadap pemerintahan Prabowo. Sayangnya, hanya DPR yang menjadi sasaran. Padahal tunjangan tersebut tidak dapat terkabulkan jika pemerintah menolak usulan DPR.
Tingginya Political Cost
Mengapa DPR gencar menuntut tunjangan rumah, padahal sudah memiliki pendapatan ratusan juta rupiah? Melompat langsung ke kesimpulan bahwa anggota DPR tamak mungkin benar, tetapi juga tendensius dan reduksionis. Moralisme cenderung memotret masalah dengan hanya dua kacamata: hitam atau putih. Padahal realitas tidak sesederhana itu, apalagi dunia politik doyan area abu-abu.
Permintaan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan sebenarnya hanya satu dari serangkaian tunjangan DPR yang tidak masuk akal. Namun, mengapa anggota DPR seolah merasa layak menuntut haknya. Aspirasi DPR sebenarnya dilandasi tingginya political cost untuk menjadi anggota dewan di Indonesia.
Untuk bertarung dalam Pemilu Legislatif (Pileg), seorang kandidat harus membayar mahal untuk mendapatkan nomor urut, membentuk tim sukses sendiri, tim saksi di TPS, dan menyiapkan miliaran rupiah untuk serangan fajar (Aspinall & Berenschot, 2019). Belum biaya tak terduga lain. Maka, tidak heran jika pasca kemenangan, yang dikejar para anggota DPR adalah balik modal, bukan memupuk amal perbuatan baik.
Kondisi semacam ini memaksa anggota dewan untuk memandang politik tidak lebih dari transaksi di pasar. Tidak seorang pun ingin merugi di dalam bertransaksi. Pileg adalah investasi yang riskan, tetapi jalan ninja untuk menjadi kaya. Jika seorang caleg terpilih, ia memperoleh gaji dan tunjangan fantastis. Jaringan bisnis diproteksi dan diperluas. Suntikan dana dari oligarki pun mengalir untuk meminta proteksi kekuasaan politik atas ladang bisnis dan kekayaan mereka (Winters, 2014).
Menukik Lebih Dalam
Bermain politik uang bukan kehendak personal seorang caleg. Siapapun terpaksa ikut terjerumus ke dalam language games pertarungan politik ini agar tidak tereliminasi. Ada semacam prisoner's dilemma di sini: jika politisi A tidak menggunakan politik uang, dia akan mudah kalah dari politisi N yang menggunakan politik uang.
Politik uang sebenarnya adalah perjudian lama di Indonesia, tetapi baru menjadi masif sejak fajar Reformasi menyingsing. Semasa Orde Baru, para oligarki dari tingkat pusat hingga lokal tidak tertarik masuk dunia politik karena sudah diproteksi Soeharto sebagai satu-satunya wealth defense provider (Winters, 2011).
Pasca rontoknya Soeharto, para pebisnis hanya memiliki dua pilihan: berpolitik atau kekayaan dan jaringan bisnis digulung penguasa politik. Dari sinilah para pebisnis ramai-ramai terjun ke dalam politik, berkolusi dengan elite di level lokal hingga nasional. Rent-seeking, pork barrel, and freewheeling clientelism membeludak (Aspinall & Sukmajati, 2016).
Orang bertarung di dalam arena politik di Republik ini juga karena domain politik menjadi satu-satunya primadona. Indonesia sangat paternalistik, mengatur semua hal: dari ruang privat seperti perkawinan hingga ruang publik. Yang paling keliru adalah intervensi negara terhadap pasar yang tidak lagi pada level mencegah market failure tetapi justru mengganggu. BUMN menguasai arena bisnis.
Investasi tidak bergantung sistem hukum, tetapi siapa penguasa. Maka, siapapun yang berada di tampuk pemerintahan berkuasa untuk mengatur semua aspek hidup orang.
Solusi Alternatif
Kedua akar masalah di atas menuntut penyelesaian sistematis ekonomi politik, bukan sekadar membatalkan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Kembali ke muruah demokrasi penuh sebenarnya adalah jalan keluar yang patut dipertimbangkan.
Demokrasi liberal memang tengah mengalami pasang surut secara global (Diamond, 2015). Namun, itu bukan karena sistem demokrasi mengalami krisis nilai, melainkan kelompok anti-demokrasi liberal pandai mengimitasi dan mengeksploitasi kelemahan demokrasi untuk tetap bertengger di kursi kekuasaan (Morgenbesser, 2020).
Di Indonesia orang menolak demokrasi liberal dengan alasan tidak sesuai budaya khas Indonesia, nilai-nilai Asia. Padahal nilai-nilai Asia justru lebih sebagai propaganda politik anti-Barat daripada representasi kultural (Fukuyama, 1995). Nilai-nilai demokrasi liberal bersifat universal (Sen, 1997). Studi empiris menunjukkan nilai-nilai Asia justru tidak seluruhnya menafikan demokrasi liberal (Ho, 2023).
Kombinasi kreatif demokrasi liberal dan nilai Asia dapat menjadi alternatif solusi terhadap praktik demokrasi selama ini (Shin, 2012). Salah satunya adalah pemilihan DPR menggunakan dua mekanisme: sebagian melalui Pileg, sebagian lagi melalui tes kompetensi secara ketat.
Untuk caleg jalur tes, hanya peserta yang memiliki kompetensi teknis, etis, dan kepemimpinan yang dapat dipilih (Bowman, 2010). Selain itu, negara-negara demokrasi maju selalu menarik demarkasi jelas antara pasar dan negara. Klaim bahwa intervensi negara adalah jalan keluar terhadap market failure adalah falasi (Pennington, 2000). Bagaimana mungkin negara dapat menyelamatkan pasar jika politisi lebih mementingkan kepentingan diri dan jangka pendek daripada pebisnis? Maka, intervensi negara terhadap pasar harus terbatas pada menyediakan kerangka hukum yang ramah investasi, menghargai property rights, mencegah monopoli dan oligopoli, dan memastikan hukum ini berjalan.
Usulan membubarkan DPR tidak berdasar di dalam sistem demokrasi (Montesquieu, 1748). Kehadiran lembaga legislatif krusial untuk menyeimbangkan dan mencegah kekuasaan absolut di tangan eksekutif. Maka, alih-alih membubarkan DPR, lebih baik mengubah mekanisme perekrutan DPR untuk memastikan anggotanya akuntabel terhadap para pemilih.
Jangan berharap memiliki anggota DPR sekelas Eropa Barat yang berkebajikan jika cara bajingan yang kita pakai untuk memilih anggota dewan. Kebajikan tidak diturunkan dari langit tetapi dikonstruksi secara sosial. (H-3)

 6 hours ago
4
6 hours ago
4










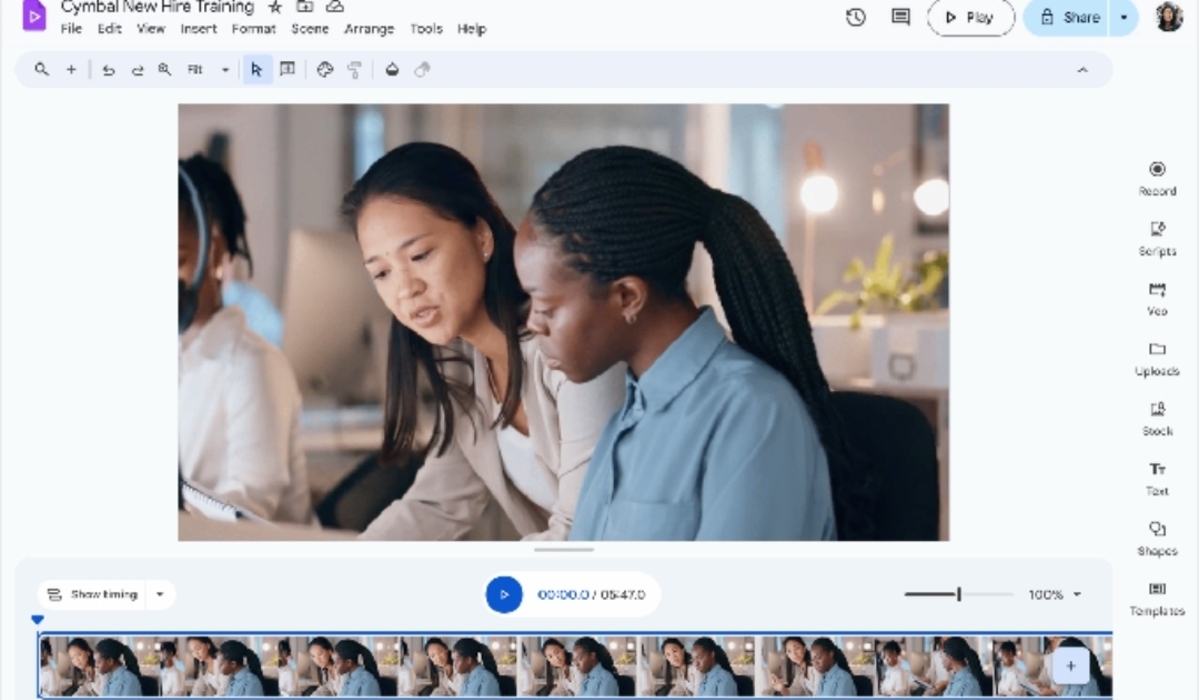






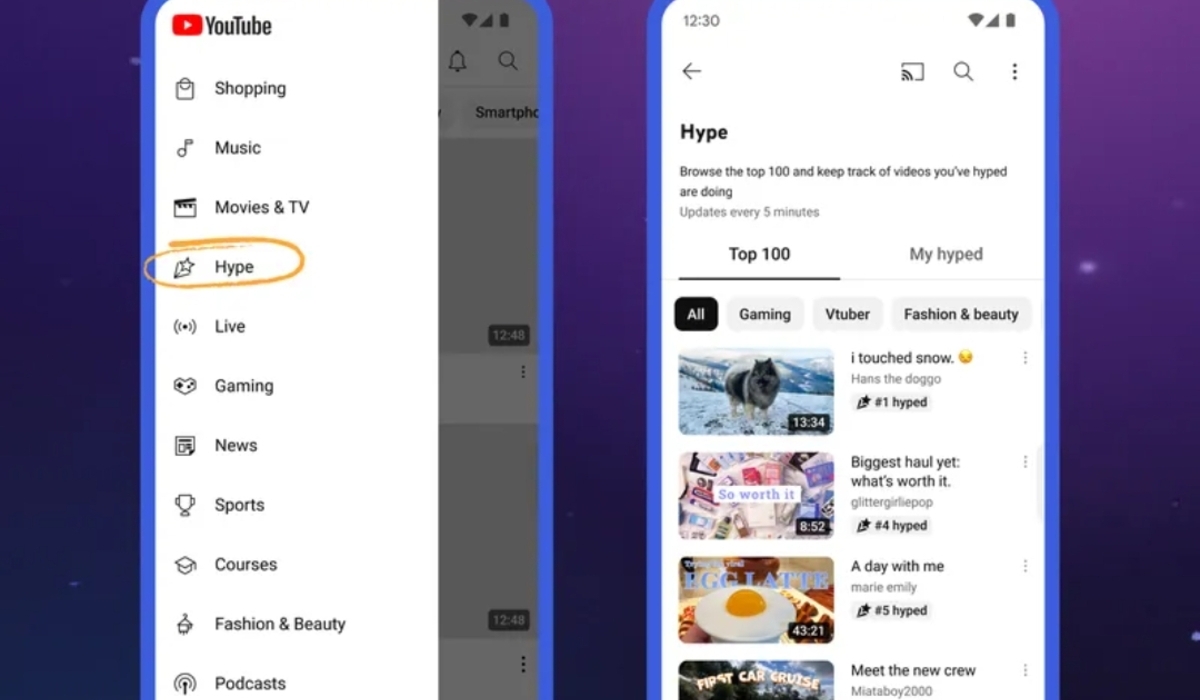

















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5283195/original/083919800_1752546684-El_Rumi_vs_Jefri_Nichol_-_SKO_3.jpg)



